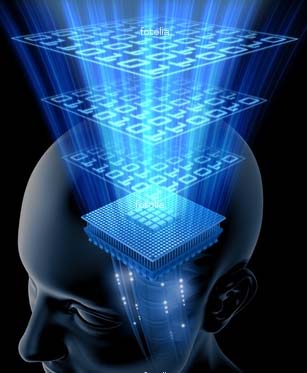Jangan Cari Aku di Facebook-mu
Apakah Facebook? Mahluk apakah ia, hingga namanya hari ini kian dengan mudah kita dengar di mana-mana? Kekuatan apa pula yang membuatnya hari ini mampu menarik 2 juta orang dari seluruh dunia sebagai users account baru setiap minggunya, bergerak kian meningkat pesat dibandingkan laman sejenisnya?
Apakah Facebook semata kita definisikan sebagai salah satu laman jejaring pertemanan di dunia maya, seperti halnya Friendster, Plurk, Twitter, dan lainnya? Ataukah ia bisa juga menunjukkan fenomena sosial yang mengacu pada perubahan tingkah laku masyarakat dunia?
Lalu siapa sesungguhnya Mark Zuckerberg yang mulai mengembangkan Facebook dengan bahasa pemrograman Ruby On Rails di usianya ke 21 tahun itu? Dan kenapa juga tulisan ini mesti saya beri judul “Jangan Cari Aku di Facebook-mu”, seakan-akan saya hendak menularkan sebentuk kesinisan usang yang tak laku zaman tentang perilaku kegandrungan manusia akan Facebook di era cyber saat ini?
Mari kita jawab satu persatu pertanyaan di atas…
Facebook Sebagai Wadah Sosial
"Facebook adalah wadah sosial yang menghubungkan seseorang dengan teman serta orang lain yang bekerja, belajar, dan hidup di sekitarnya." Begitu kalimat pembuka yang saya jumpai pertengahan tahun lalu ketika pertama kali masuk ke halaman utama Facebook.com.
Dan segera setelah itu, saya sukses membuat sebuah akun atas nama saya di sana. Terasa menyenangkan memang, pada awalnya Facebook mampu ‘menghubungkan’ saya dengan banyak kawan baru, bersosialisasi, bahkan berkumpul lagi, dan berdiskusi dengan kawan-kawan lama yang sudah bertahun-tahun tak pernah ketemu.
Yang menarik bagi saya saat itu, saat tersadar bahwa sebagian besar kawan-kawan saya para penghuni Facebook itu rata-rata menghabiskan minimal 30 menit sehari beraktivitas di sana. Entah sekedar memperbaiki status di wall-nya, mengunggah foto-foto narsis terbaru mereka, ada pula yang rajin menulis puisi dan catatan harian untuk sekedar dikomentari kawan-kawannya.
Lagipula siapa yang tahu bahwa di balik “username” tertentu di antara daftar kawan-kawan saya tersebut, beroperasi sebuah penopengan realitas akan keaslian jati diri mereka sendiri di dunia nyata. Dalam artian, siapa saja bisa menjadi apa saja dalam dunia Facebook!
Orang pun tak mampu lagi membedakan mana yang selebritis betulan dan mana yang freak, sebab dua-duanya bisa sama-sama eksis dan tenar di dunia Facebook. Karenanya dalam konteks ini, bisa dibilang bahwa Facebook merupakan semua mimpi dari representasi dan rekreasi realitas penggunanya.
Dan hal tersebut mulai terasa aneh saat saya tersadar bahwa di antara sesama penghuni Facebook sendiri, rupanya mulai terbangun pola rutinitas harian mereka di sana. Seakan-akan mereka semua bertetangga, bersosialisasi dan hidup normal layaknya di dunia nyata. Tak pelak lagi, lambat-laun saya pun curiga bahwa makin hari Facebook mulai terasa seperti sebuah dunia yang berdiri sendiri dan kian terpisah dari realitas sosial sehari-hari penggunanya.
Apakah mungkin bahwa gambaran Facebook sebagai candu masyarakat cyber kita belakangan ini, sejalan dengan yang dulu pernah diracaukan Baudrillard lewat filsafat metaforiknya tentang sebuah kematian sosial (“death of the social”)?
Facebook Sebagai Hantu Sosial
Bagi Baudrillard, kematian sosial di sini bisa kita pahami ketika ide tentang wujud sosial dan masyarakat diambil-alih oleh kuasa media dan informasi massa. Lenyapnya ide sosial dan masyarakat di sini mestilah dipicu dengan berkembangnya model-model sosial semu (artificial communities atau virtual society) yang terbentuk dari relasi, interaksi, dan komunikasi yang bersifat artifisial, sebagaimana yang tengah terjadi di dunia Facebook.
Lalu setelah relasi sosial tak lagi mengada dan kenyataan sosial habis terserap di dalamnya, apa yang kini tersisa, kawan? Jawabnya tak bisa lain adalah simulakrum sosial itu sendiri! Hahaha... Baru sekarang bisa saya bayangkan betapa naifnya Marx ketika bermimpi bahwa suatu hari nanti di masa depan, kekuatan ekonomi masyarakat bisa menopang kehidupan sosial yang komunal dan egaliter.
Kenapa naif? Karena Facebook tak hanya menunjukkan sebuah kematian sosial yang sedang terjadi di depan mata kepala saya saat ini, tapi juga membuktikan bahwa dimensi sosial itu sendiri bisa dijual. Di mana nilai-nilai keakraban dan kebersamaan komunitas itu sendiri menjadi komoditi yang diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan.
Dalam artian juga, siapa saja bisa menjadi apa saja dalam dunia Facebook selama dia tak keberatan dibombardir berbagai iklan produk dari semisal Coca-Cola dan Microsoft. Kalau masih tak percaya, simak saja niat CEO sekaligus pendiri Facebook Mark Zuckerberg pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos yang menyatakan bahwa, "Pada 2009 ini, Facebook akan intensif untuk mencari uang dengan memanfaatkan database anggota dengan lebih serius menggarap iklan." (03/02, Tempointeraktif.com)
Maka alih-alih sekedar menjadi wadah sosial yang menghubungkan seseorang dengan bla…bla...bla..., rupanya tampak jelas sekali bahwa Facebook merupakan eksperimen mutakhir para penggiat kapitalisme tingkat lanjut.
Kalau kasarnya saya bicara, Facebook bukanlah laman jejaring sosial yang murni menghubungkan para penggunanya. Tapi ini tentang bagaimana sebuah perusahaan kapitalis bisa membuat komunitas global nan artifisial yang melewati batas-batas antar negara, dan menjual produk seperti Coca-Cola kepada jutaan user-nya. Dan ini juga tentang bagaimana perusahaan kapitalis bisa menghasilkan uang banyak dari pertemanan para user-nya itu sendiri.
Penutup
Sampai di titik ini, akan sangat mungkin bila kawan-kawan pembaca menganggap saya ini semacam pemikir radikal yang post-Marxist dan menganut sikap kritis tertentu terhadap perkembangan kapitalisme mutakhir. Judul esai ini yang berbunyi “Jangan Cari Aku di Facebook-mu”, bisa saja diartikan kawan-kawan bahwa penulis di sini adalah orang yang telah dibangkitkan kesadarannya untuk keluar dari jebakan kapitalisme dengan cara menghapus akun Facebook yang dibuatnya setengah tahun yang lalu.
Kalau betul kawan-kawan menduga seperti itu, bisa saya pastikan kalian keliru. Alih-alih bersuntuk-suntuk ria dengan segala tetek bengek pemikiran kritis tentang Facebook dan kematian realitas sosial, saya justru begitu bersemangat menghanyutkan diri dalam ironi yang terlanjut fatal ini.
Hanya saja kali ini, bukan diri saya yang asli yang tampil dalam drama semu nan banal berjudul Facebook itu. Meminjam bahasa Nuruddin Asyadhie yang bilang bahwa Facebook adalah novel polifonis dunia cyber, maka bolehlah jika kali ini saya kembali menjadi salah satu tokoh di novel tersebut, tentu dengan karakter tokoh dan alur cerita yang saya kehendaki sendiri.
Maka jangan cari aku di Facebook-mu, kawan. Sebab siapa tahu saya di sana sudah jadi seseorang lain yang boleh jadi tak pernah kamu kenal sebelumnya.
Apakah Facebook semata kita definisikan sebagai salah satu laman jejaring pertemanan di dunia maya, seperti halnya Friendster, Plurk, Twitter, dan lainnya? Ataukah ia bisa juga menunjukkan fenomena sosial yang mengacu pada perubahan tingkah laku masyarakat dunia?
Lalu siapa sesungguhnya Mark Zuckerberg yang mulai mengembangkan Facebook dengan bahasa pemrograman Ruby On Rails di usianya ke 21 tahun itu? Dan kenapa juga tulisan ini mesti saya beri judul “Jangan Cari Aku di Facebook-mu”, seakan-akan saya hendak menularkan sebentuk kesinisan usang yang tak laku zaman tentang perilaku kegandrungan manusia akan Facebook di era cyber saat ini?
Mari kita jawab satu persatu pertanyaan di atas…
Facebook Sebagai Wadah Sosial
"Facebook adalah wadah sosial yang menghubungkan seseorang dengan teman serta orang lain yang bekerja, belajar, dan hidup di sekitarnya." Begitu kalimat pembuka yang saya jumpai pertengahan tahun lalu ketika pertama kali masuk ke halaman utama Facebook.com.
Dan segera setelah itu, saya sukses membuat sebuah akun atas nama saya di sana. Terasa menyenangkan memang, pada awalnya Facebook mampu ‘menghubungkan’ saya dengan banyak kawan baru, bersosialisasi, bahkan berkumpul lagi, dan berdiskusi dengan kawan-kawan lama yang sudah bertahun-tahun tak pernah ketemu.
Yang menarik bagi saya saat itu, saat tersadar bahwa sebagian besar kawan-kawan saya para penghuni Facebook itu rata-rata menghabiskan minimal 30 menit sehari beraktivitas di sana. Entah sekedar memperbaiki status di wall-nya, mengunggah foto-foto narsis terbaru mereka, ada pula yang rajin menulis puisi dan catatan harian untuk sekedar dikomentari kawan-kawannya.
Lagipula siapa yang tahu bahwa di balik “username” tertentu di antara daftar kawan-kawan saya tersebut, beroperasi sebuah penopengan realitas akan keaslian jati diri mereka sendiri di dunia nyata. Dalam artian, siapa saja bisa menjadi apa saja dalam dunia Facebook!
Orang pun tak mampu lagi membedakan mana yang selebritis betulan dan mana yang freak, sebab dua-duanya bisa sama-sama eksis dan tenar di dunia Facebook. Karenanya dalam konteks ini, bisa dibilang bahwa Facebook merupakan semua mimpi dari representasi dan rekreasi realitas penggunanya.
Dan hal tersebut mulai terasa aneh saat saya tersadar bahwa di antara sesama penghuni Facebook sendiri, rupanya mulai terbangun pola rutinitas harian mereka di sana. Seakan-akan mereka semua bertetangga, bersosialisasi dan hidup normal layaknya di dunia nyata. Tak pelak lagi, lambat-laun saya pun curiga bahwa makin hari Facebook mulai terasa seperti sebuah dunia yang berdiri sendiri dan kian terpisah dari realitas sosial sehari-hari penggunanya.
Apakah mungkin bahwa gambaran Facebook sebagai candu masyarakat cyber kita belakangan ini, sejalan dengan yang dulu pernah diracaukan Baudrillard lewat filsafat metaforiknya tentang sebuah kematian sosial (“death of the social”)?
Facebook Sebagai Hantu Sosial
Bagi Baudrillard, kematian sosial di sini bisa kita pahami ketika ide tentang wujud sosial dan masyarakat diambil-alih oleh kuasa media dan informasi massa. Lenyapnya ide sosial dan masyarakat di sini mestilah dipicu dengan berkembangnya model-model sosial semu (artificial communities atau virtual society) yang terbentuk dari relasi, interaksi, dan komunikasi yang bersifat artifisial, sebagaimana yang tengah terjadi di dunia Facebook.
Lalu setelah relasi sosial tak lagi mengada dan kenyataan sosial habis terserap di dalamnya, apa yang kini tersisa, kawan? Jawabnya tak bisa lain adalah simulakrum sosial itu sendiri! Hahaha... Baru sekarang bisa saya bayangkan betapa naifnya Marx ketika bermimpi bahwa suatu hari nanti di masa depan, kekuatan ekonomi masyarakat bisa menopang kehidupan sosial yang komunal dan egaliter.
Kenapa naif? Karena Facebook tak hanya menunjukkan sebuah kematian sosial yang sedang terjadi di depan mata kepala saya saat ini, tapi juga membuktikan bahwa dimensi sosial itu sendiri bisa dijual. Di mana nilai-nilai keakraban dan kebersamaan komunitas itu sendiri menjadi komoditi yang diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan.
Dalam artian juga, siapa saja bisa menjadi apa saja dalam dunia Facebook selama dia tak keberatan dibombardir berbagai iklan produk dari semisal Coca-Cola dan Microsoft. Kalau masih tak percaya, simak saja niat CEO sekaligus pendiri Facebook Mark Zuckerberg pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos yang menyatakan bahwa, "Pada 2009 ini, Facebook akan intensif untuk mencari uang dengan memanfaatkan database anggota dengan lebih serius menggarap iklan." (03/02, Tempointeraktif.com)
Maka alih-alih sekedar menjadi wadah sosial yang menghubungkan seseorang dengan bla…bla...bla..., rupanya tampak jelas sekali bahwa Facebook merupakan eksperimen mutakhir para penggiat kapitalisme tingkat lanjut.
Kalau kasarnya saya bicara, Facebook bukanlah laman jejaring sosial yang murni menghubungkan para penggunanya. Tapi ini tentang bagaimana sebuah perusahaan kapitalis bisa membuat komunitas global nan artifisial yang melewati batas-batas antar negara, dan menjual produk seperti Coca-Cola kepada jutaan user-nya. Dan ini juga tentang bagaimana perusahaan kapitalis bisa menghasilkan uang banyak dari pertemanan para user-nya itu sendiri.
Penutup
Sampai di titik ini, akan sangat mungkin bila kawan-kawan pembaca menganggap saya ini semacam pemikir radikal yang post-Marxist dan menganut sikap kritis tertentu terhadap perkembangan kapitalisme mutakhir. Judul esai ini yang berbunyi “Jangan Cari Aku di Facebook-mu”, bisa saja diartikan kawan-kawan bahwa penulis di sini adalah orang yang telah dibangkitkan kesadarannya untuk keluar dari jebakan kapitalisme dengan cara menghapus akun Facebook yang dibuatnya setengah tahun yang lalu.
Kalau betul kawan-kawan menduga seperti itu, bisa saya pastikan kalian keliru. Alih-alih bersuntuk-suntuk ria dengan segala tetek bengek pemikiran kritis tentang Facebook dan kematian realitas sosial, saya justru begitu bersemangat menghanyutkan diri dalam ironi yang terlanjut fatal ini.
Hanya saja kali ini, bukan diri saya yang asli yang tampil dalam drama semu nan banal berjudul Facebook itu. Meminjam bahasa Nuruddin Asyadhie yang bilang bahwa Facebook adalah novel polifonis dunia cyber, maka bolehlah jika kali ini saya kembali menjadi salah satu tokoh di novel tersebut, tentu dengan karakter tokoh dan alur cerita yang saya kehendaki sendiri.
Maka jangan cari aku di Facebook-mu, kawan. Sebab siapa tahu saya di sana sudah jadi seseorang lain yang boleh jadi tak pernah kamu kenal sebelumnya.

Jangan Biarkan Facebook Membombardir Email Anda
Setelah anda mempunyai sebuah profil di Facebook, sudah seharusnya anda mengubah beberapa setting default yang ditetapkan oleh Facebook. Satu yang terpenting adalah setting tentang email notifikasi yang bakal anda terima lewat email anda. Pada kondisi default Facebook memberikan opsi ON atas semua notifikasi, itu artinya anda bakal dibanjiri email dari Facebook, hingga inbox andapun akan penuh dengan email-email notifikasi yang kadangkala ngga penting.
Untuk mengubah setting tentang notifikasi ini bisa anda akses lewat menu [setting] > [account setting] anda akan dibawa ke halaman My Account, setelah itu anda klik tab [notification]. Bisa anda lihat, di sana banyak sekali notifikasi yang disediakan oleh Facebook untuk dikirim ke email anda. Mulai dari notifikasi tentang Photos, Groups, Pages, Video sampai kepada notifikasi yang berkaitan dengan Help Centre. Dan dalam keadaan default Facebook meng-ON-kan semuanya!
Sekarang waktunya anda untuk memilah dan memilih poin-poin mana saja yang penting, yang memang layak untuk dikirimkan notifikasinya ke email anda bila terjadi update pada poin tersebut. Misal, bila anda menginginkan Facebook memberikan notifikasi bila ada pesan dari Friends anda di Facebook, maka berilah tanda ON pada “Send me a message”. Kemudian bila anda mengganggap bahwa semua hal yang berkaitan dengan Help Centre itu ngga penting, maka berilah tanda OFF pada “Replies to my Help Center questions”.
Sumber
Setelah anda mempunyai sebuah profil di Facebook, sudah seharusnya anda mengubah beberapa setting default yang ditetapkan oleh Facebook. Satu yang terpenting adalah setting tentang email notifikasi yang bakal anda terima lewat email anda. Pada kondisi default Facebook memberikan opsi ON atas semua notifikasi, itu artinya anda bakal dibanjiri email dari Facebook, hingga inbox andapun akan penuh dengan email-email notifikasi yang kadangkala ngga penting.
Untuk mengubah setting tentang notifikasi ini bisa anda akses lewat menu [setting] > [account setting] anda akan dibawa ke halaman My Account, setelah itu anda klik tab [notification]. Bisa anda lihat, di sana banyak sekali notifikasi yang disediakan oleh Facebook untuk dikirim ke email anda. Mulai dari notifikasi tentang Photos, Groups, Pages, Video sampai kepada notifikasi yang berkaitan dengan Help Centre. Dan dalam keadaan default Facebook meng-ON-kan semuanya!
Sekarang waktunya anda untuk memilah dan memilih poin-poin mana saja yang penting, yang memang layak untuk dikirimkan notifikasinya ke email anda bila terjadi update pada poin tersebut. Misal, bila anda menginginkan Facebook memberikan notifikasi bila ada pesan dari Friends anda di Facebook, maka berilah tanda ON pada “Send me a message”. Kemudian bila anda mengganggap bahwa semua hal yang berkaitan dengan Help Centre itu ngga penting, maka berilah tanda OFF pada “Replies to my Help Center questions”.
Sumber